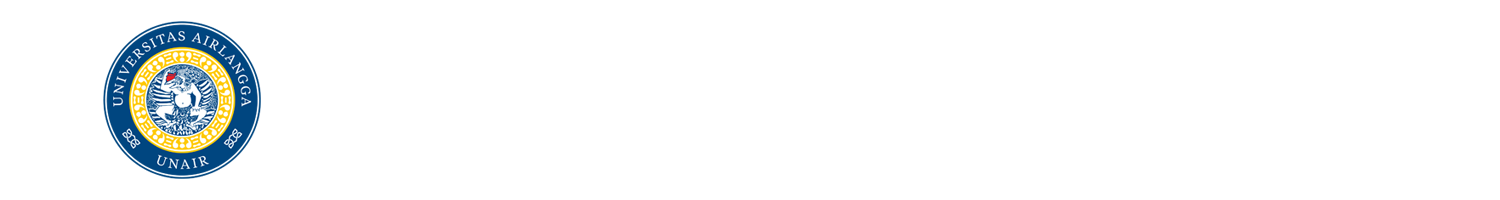Jalan Panjang yang Belum Usai: Menuju Kemandirian Produksi Obat di Indonesia

Oleh : Prof. Dr. Hery Suwito, M.Si
DATA impor Bahan Baku Obat (BBO) yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir adalah US $ 443 juta (2021), US $ 509 juta (2022), dan US $ 1,27 miliar (2023). Negara utama pengimpor bahan baku tersebut adalah Cina (45%), India (27%), dan Amerika Serikat (8%), sisa 20% berasal dari negara lain. Meskipun terjadi penurunan volume impor pada tahun 2023, ketergantungan impor BBO tetap tinggi, mencapai lebih dari 90% pada tahun 2024.
Pemenuhan BBO tidak semuanya diimpor. Sebagian kecil obat tersebut sudah ada yang diproduksi di Indonesia, walaupun tidak melalui total sintesis, artinya diproduksi BBO dari bahan kimia yang sederhana. Proses produksi tersebut biasanya dilakukan pada tahap akhir reaksi, sedang bahan baku yang diperlukan untuk sintesis tahap akhir reaksi tersebut tetap masih diimpor.
Jadi belum dilakukan sintesis bahan baku obat dari bahan dasar yang sederhana yang berasal dari produksi dalam negeri. Selain itu, ada tambahan biaya produksi yang harus dibayar, yaitu biaya paten dari metode produksi yang digunakan.
Salah satu solusi yang bisa ditawarkan bagi pemecahan masalah produksi BBO ini adalah memproduksi BBO yang berbahan dasar dari dalam negeri, serta yang berfungsi ganda, yaitu berguna sebagai obat dan sebagai bahan antara untuk memproduksi bahan obat dengan aktivitas lain.
Selanjutnya metode produksi bahan tersebut telah bebas dari biaya paten, yang bisa diperoleh dari metode produksi yang telah melampaui batas kewajiban pembayaran biaya paten (sudah terdaftar paten pada waktu yang sudah lama).
Produksi BBO sederhana yang memenuhi kriteria tersebut adalah produksi asam salisilat. Asam salisilat dapat diproduksi menggunakan reaksi Kolbe-Schmitt dari bahan baku fenol dan sodium hidroksida, yang dilanjutkan penambahan gas karbon dioksida (CO2).
Fenol merupakan alkohol aromatis yang diperoleh dari benzena, sedang benzena dapat diperoleh dari minyak bumi. Terdapat 4 perusahaan yang memproduksi fenol di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 125.250 ton per tahun.
Jika selama ini fenol tersebut belum banyak digunakan untuk produksi bahan farmasi, terobosan ini merupakan suatu usaha diversifikasi aplikasi fenol yang lain. Sedangkan untuk sodium hidroksida, Indonesia memiliki kapasitas produksi sebesar 1.306.000 ton per tahun dari 8 perusahaan kimia.
Salah satu produsen utama karbondioksida cair di Indonesia adalah PT Pupuk Kujang yang diproduksi dengan memanfaatkan gas ekses dari produksi pupuk, dengan kapasitas produksi mencapai 50.000 ton CO2 cair pertahun, dengan kemurnian CO2 yang dihasilkan hingga 99,9%. Data ini memperlihatkan bahwa bahan dasar yang diperlukan untuk memproduksi asam salisilat dapat diperoleh dalam negeri.
Pada proses produksi asam salisilat menggunakan reaksi Kolbe-Schmitt, mula-mula adalah mereaksikan fenol dengan sodium hidroksida untuk membentuk sodium fenoksida, sedang air yang terbentuk diuapkan. Tahap berikutnya adalah dengan mengalirkan gas CO2 ke dalam bejana reaksi, dan campuran reaksi dipanaskan pada suhu sekitar 100-1300C dan tekanan 5-7 atm. Garam sodium salisilat yang terbentuk selanjutnya dinetralkan menggunakan asam kuat (asam klorida atau asam sulfat), sehingga asam salisilat yang dikehendaki mengendap.
Setelah melalui penyaringan, akan diperoleh asam salisilat dengan kemurnian lebih dari 90%. Reaksi Kolbe-Schmitt ini dipatenkan oleh 2 ilmuwan Jerman, yaitu Hermann Kolbe dan Rudolph Schmitt pada tahun 1860. Oleh sebab itu, paten ini sudah kadaluarsa dan bisa dipakai dengan bebas.
Dalam bidang medis, asam salisilat biasanya digunakan untuk pengobatan masalah kulit (mengangkat lapisan kulit mati, kapalan, kutil dan eksim), mengurangi peradangan, serta digunakan sebagai ban baku obat lain.
Berikut ini disampaikan obat lain berbahan baku asam salisilat. Salisilamida merupakan turunan asam salisilat yang digunakan sebagai obat analgesik (pereda nyeri), dan antipiretik (penurun demam). Kombinasi salisilamida dengan kafein digunakan sebagai obat flu, atau pilek.
Salsalate merupakan dimer asam salisilat yang biasanya dipakai sebagai obat antiperadangan kronis, terutama rematik arthritis dan osteoarthritis. Obat ini memiliki keunggulan, yaitu menimbulkan efek iritasi lambung lebih sedikit dibanding dengan aspirin.
Selanjutnya adalah sulfasalazine, yang biasa digunakan sebagai obat radang usus, rheumatic arthritis, dan imunomodulator. Yang terakhir adalah diflunisal, yang biasa dipakai sebagai obat analgesik (pereda nyeri), dan antiinflamasi.
Dapat disimpulkan bahwa pemilihan produksi asam salisilat dapat dijadikan tahap awal produksi obat berbahan baku dari dalam negeri. Selain itu, asam salisilat juga merupakan bahan antara yang menjadi bahan baku bagi produksi obat lain yang berbasis asam salisilat. (Penulis adalah Guru Besar Bidang Desain dan Sintesis Senyawa Bioaktif, Fakultas Sains dan Teknologi – Universitas Airlangga)
Diunggah kembali oleh admin dari sumber : Jalan Panjang yang Belum Usai: Menuju Kemandirian Produksi Obat di Indonesia | jurnalindonesia.net